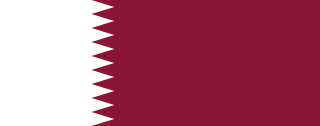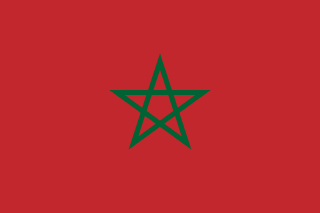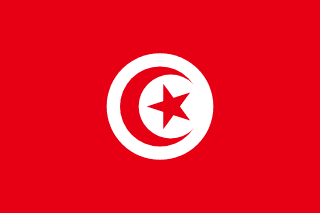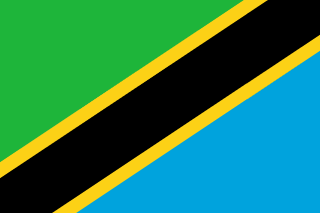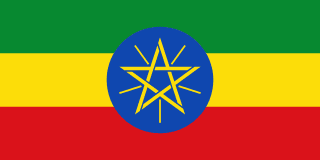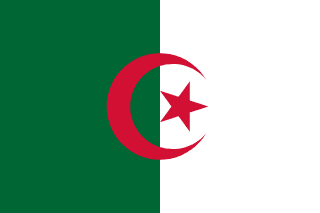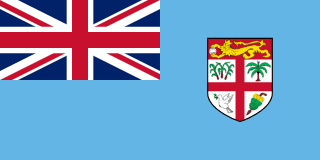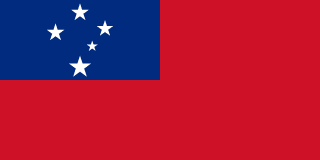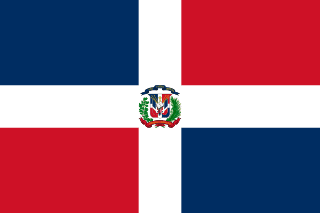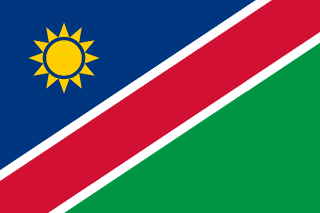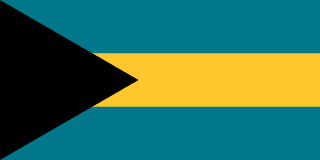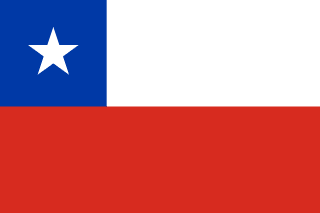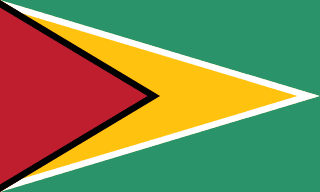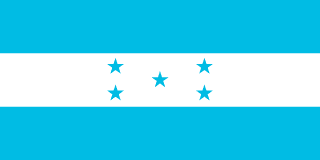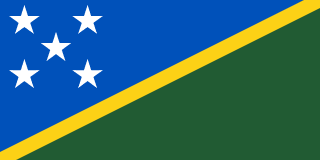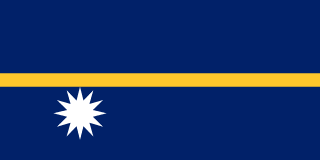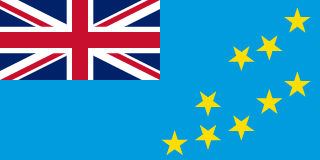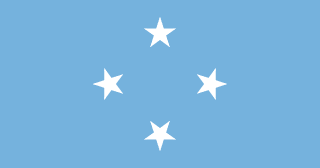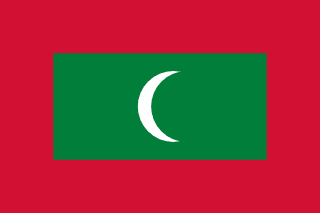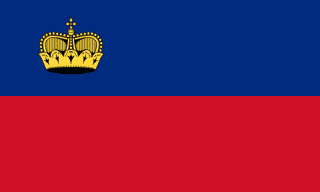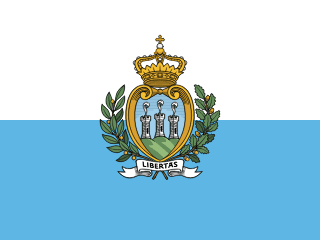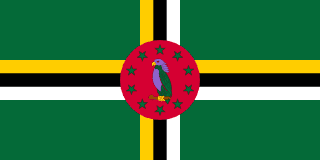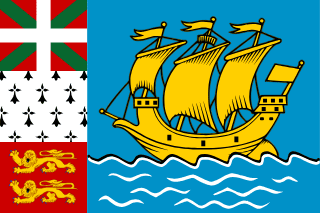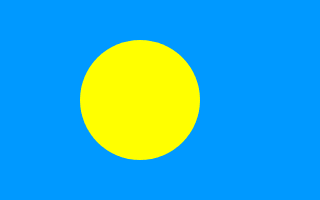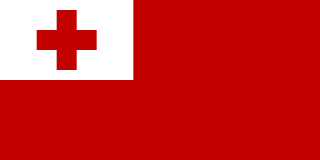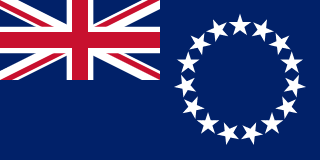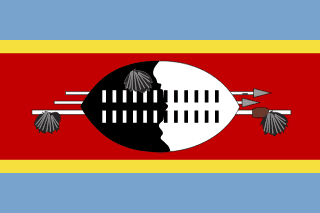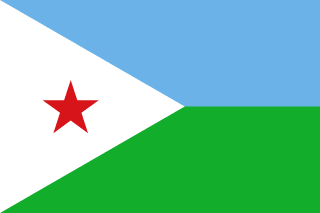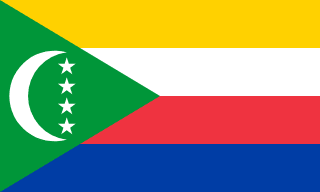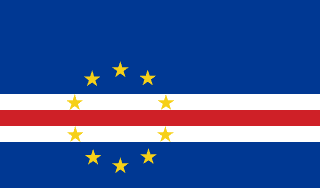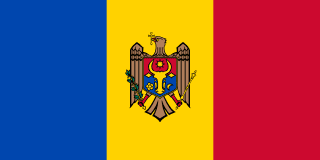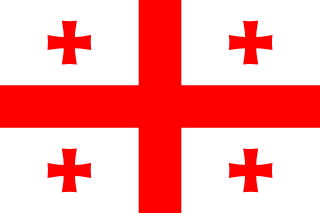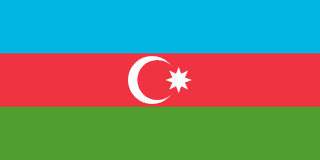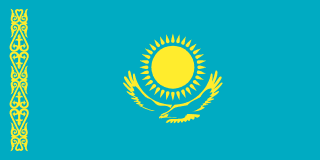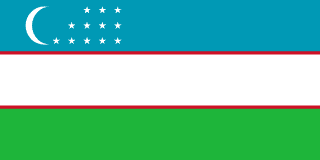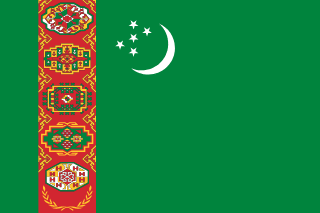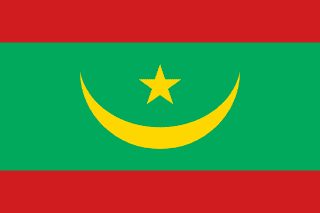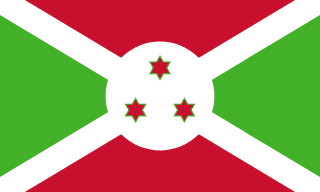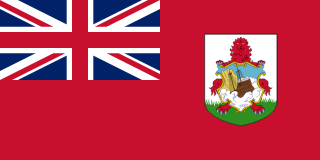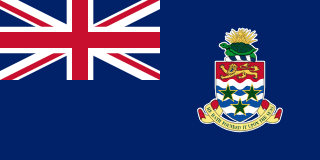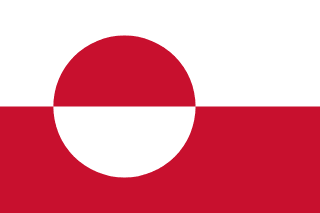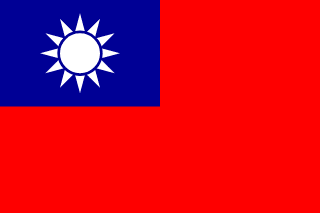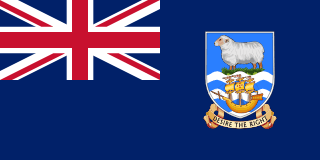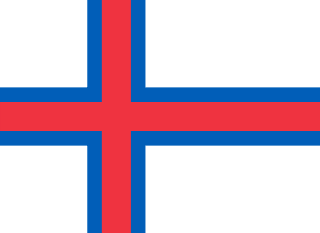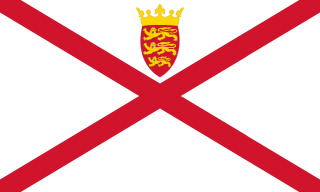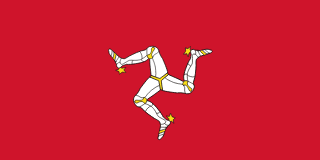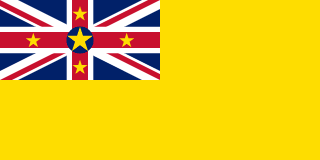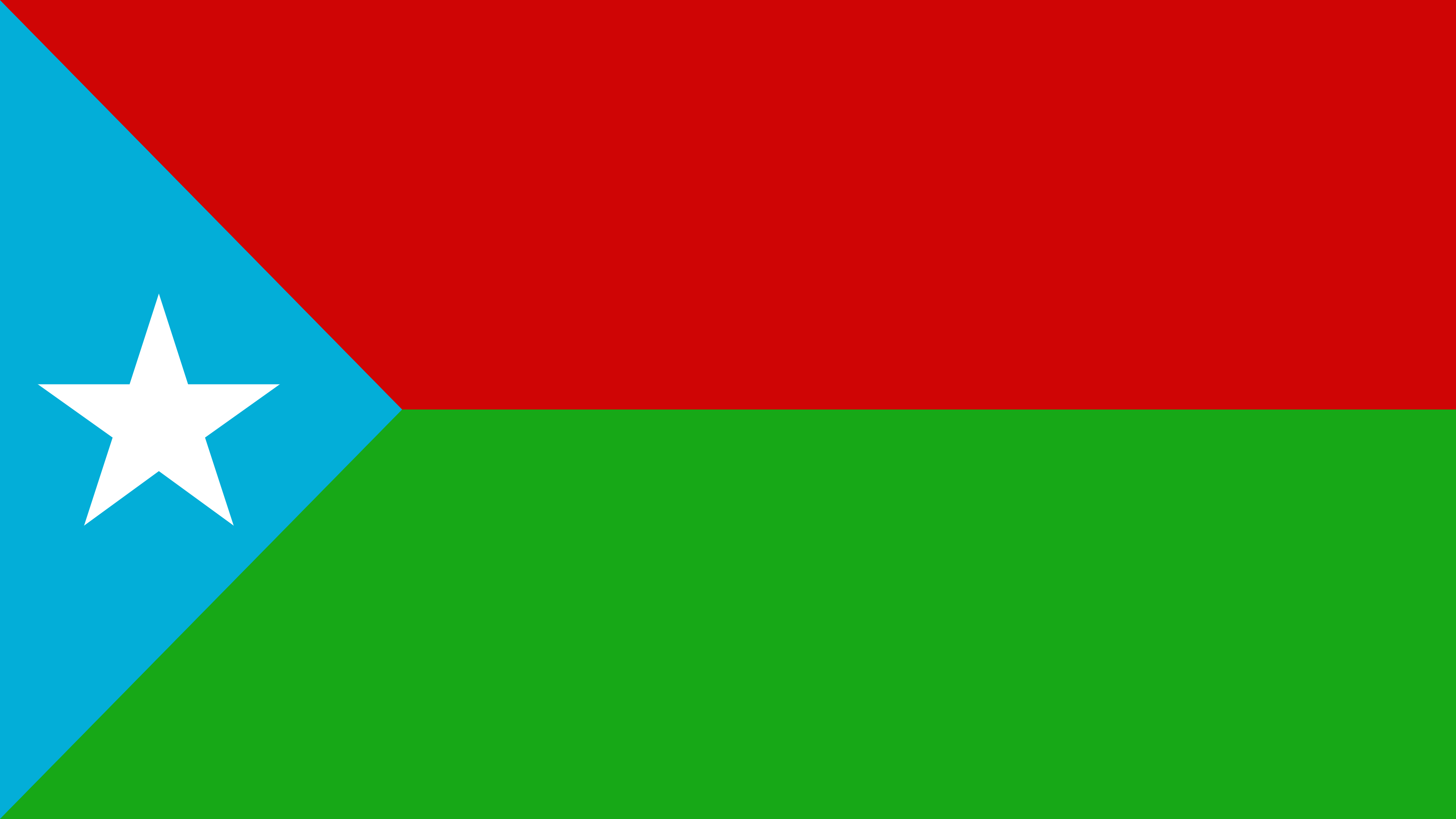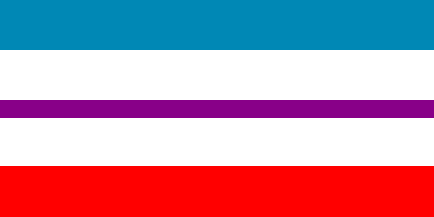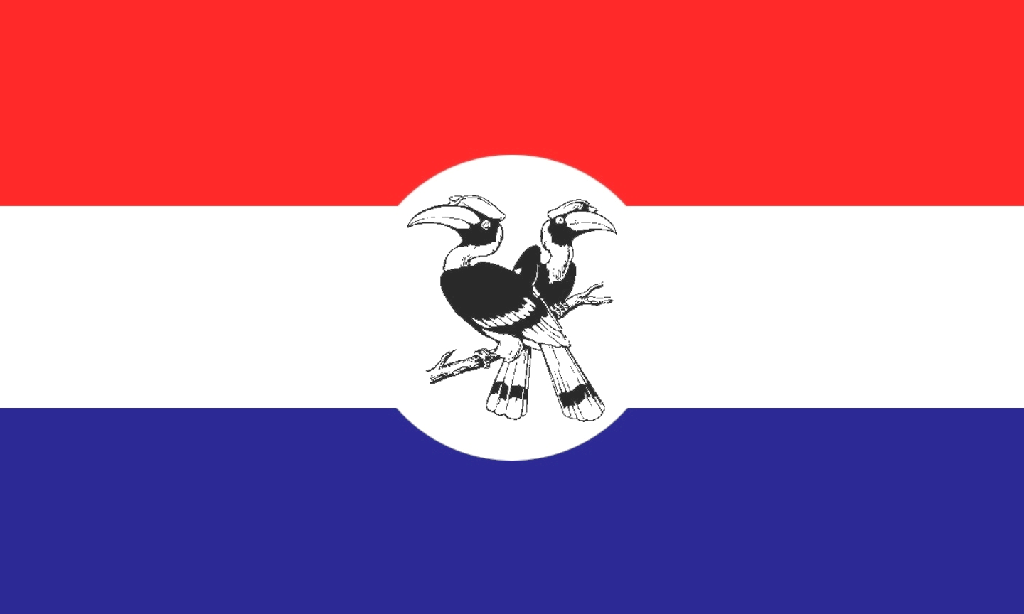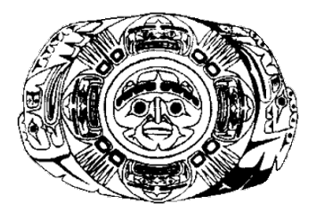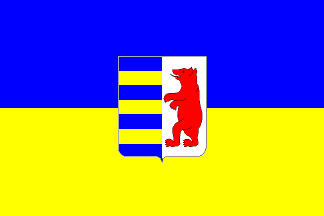Naskah Legendaris Nusantara dari Abad ke-14 hingga ke-19 yang diakui UNESCO membuka jendela pada ingatan kolektif kepulauan Nusantara, dari epos Bugis La Galigo, teks didaktik Sunda Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, dan karya-karya sufi Hamzah Fansuri; berlanjut ke kronik istana Hikayat Aceh, otobiografi perjuangan Babad Diponegoro, hingga memori perlawanan Tambo Tuanku Imam Bonjol. Artikel ini merangkai konteks sejarah, nilai sastra dan filologis, serta status penginskripsian dalam program Memory of the World—menunjukkan bagaimana naskah-naskah tersebut bukan hanya artefak masa lampau, melainkan rujukan hidup bagi identitas budaya, kebijakan pelestarian, dan kolaborasi riset lintas negara.

La Galigo (Sureq Galigo) – Ditulis Sekitar Abad Ke-14
La Galigo adalah epos mitologis Bugis yang berakar pada tradisi lisan pra-Islam, lalu dituliskan dalam bahasa Bugis dengan metrum ketat dan kosakata puitik yang khas. Kisah penciptaan ini menautkan dunia para dewa dan manusia serta tersohor karena keluasannya: diperkirakan sekitar 6.000 halaman folio, kerap disebut salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Atas signifikansi sastrawi dan dokumenternya, La Galigo diinskripsikan pada UNESCO Memory of the World International Register tahun 2011.
Tradisi manuskrip La Galigo tersebar dan kaya varian; naskah-naskahnya ditulis dalam aksara Bugis lontaraq dan kini tersimpan di berbagai lembaga memori. Leiden University Libraries memegang salah satu korpus paling berharga dan telah mendigitalkannya sehingga peneliti dapat menelaah langsung citra halaman, struktur teks, dan varian bacaan. Digitalisasi ini—yang ditegaskan dalam rilis resmi Leiden—memudahkan riset filologi, katalogisasi, dan pengajaran, sekaligus memperkuat pelestarian jangka panjang.
Di luar ranah akademik, La Galigo menginspirasi pentas lintas-benua melalui produksi teater musik “I La Galigo” oleh Robert Wilson (perdana 2004, tur Asia–Eropa–Amerika), dengan musik garapan Rahayu Supanggah. Penerimaan internasional atas pementasan ini ikut memperluas perhatian publik pada warisan Bugis dan mendorong pembacaan ulang epos sebagai memori budaya yang hidup. Gambaran tentang skala epos—serta reputasinya sebagai salah satu yang terpanjang—kembali menegaskan alasan pengakuan UNESCO dan relevansinya bagi kajian sastra dunia.

Sang Hyang Siksa Kandang Karesian (SSKK) – Ditulis Sekitar Tahun 1518 M / 1440 Saka
SSKK adalah teks didaktik Sunda bertarikh 1518 M (1440 Saka) yang memuat petunjuk laku, moral, dan adat masyarakat Sunda. Naskahnya ditulis di atas daun gebang dan menggunakan aksara Jawa Kuno Barat (kuadratik) dalam bahasa Sunda Kuno—lapisan bahasa yang menjadi kunci memahami leksikon, wacana moral, dan konsep tatanan sosial Sunda pra-kolonial. SSKK menyajikan panduan etika yang juga mencerminkan hukum kebiasaan pada masanya.
UNESCO menginskripsikan SSKK ke MoW International Register 2025, menekankan kelangkaan media tulisnya—daun gebang—serta kedudukan naskah sebagai salah satu dari segelintir manuskrip sejenis yang masih bertahan di Indonesia. Uraian UNESCO juga menyorot bagaimana teks ini memberi cahaya pada jejaring dagang dan politik Sunda dengan berbagai kawasan Asia, sehingga nilai dokumenternya tidak hanya bersifat normatif-keagamaan, tetapi juga historis.

Karya-karya Hamzah Fansuri – Ditulis Sekitar Abad Ke-16
Korpus karya Hamzah Fansuri—penyair-sufi abad ke-16 dari kawasan Aceh—resmi diinskripsikan pada Memory of the World International Register 2025 sebagai nominasi bersama Indonesia–Malaysia. UNESCO menekankan peran Hamzah dalam “revolusi spiritual” Melayu: ia memulai tradisi kitab (tulisan ilmiah sistematis) dalam bahasa Melayu, memadukan prosa dan puisi (syair) untuk mengekspresikan ajaran tasawuf, dan meletakkan dasar perdebatan ilmiah dalam bahasa tersebut. Pengakuan ini menempatkan karya-karyanya sebagai warisan dokumenter lintas-negara yang berpengaruh bagi pembentukan khazanah intelektual Melayu–Nusantara.
Secara intelektual, Hamzah dikenal sebagai perintis penyair Melayu yang menggubah doktrin-doktrin tasawuf—terutama wahdat al-wujūd—ke dalam bentuk puitik dan prosa ajar, sembari menunjukkan kemampuan teknis pada rima, permainan kata, serta integrasi kosakata Arab–Persia ke struktur Melayu. Biografinya memang tak sepenuhnya pasti, namun tradisi riset modern menempatkannya sebagai figur kunci yang melanglang (Aceh, Semenanjung, Mughal India, Makkah–Madinah, Baghdad) dan berpengaruh besar pada jaringan intelektual Aceh awal modern. Dalam sejarah intelektual Aceh, kontroversi pemikirannya memicu kecaman—hingga pembakaran karya—oleh Nuruddin ar-Raniri pada abad ke-17, yang ironisnya justru menggarisbawahi daya-guncang gagasan Hamzah di kancah keilmuan kawasan.
Dari sisi tekstual, karya prosanya yang masyhur mencakup Sharab al-‘Ashiqin (“Minuman Para Pencinta”), Asrar al-‘Arifin (“Rahasia Para Arif”), dan Kitab al-Muntahi, sementara di ranah puisi syair seperti Syair Perahu menjadi rujukan klasik hingga kini. Di mata UNESCO, pengaruh syair Hamzah menyebar luas di Kepulauan, meletakkan landasan bagi sastra Indonesia–Malaysia modern.

Hikayat Aceh – Ditulis Sekitar Abad Ke-17
Hikayat Aceh adalah kronik istana berbahasa Melayu dalam aksara Arab-Jawi dari abad ke-17 yang berpusat pada figur Sultan Iskandar Muda (1607–1636). Teks ini memotret adat, diplomasi, perang, dan religiositas istana Aceh sekaligus memberi gambaran karakter dan kepemimpinan sang sultan. Pada 2023, tiga manuskrip Hikayat Aceh diinskripsikan ke Memory of the World International Register melalui pengajuan bersama Indonesia–Belanda, menegaskan nilainya sebagai sumber primer bagi sejarah politik-budaya Aceh awal modern.
Dari segi gaya dan tujuan penulisan, Hikayat Aceh memadukan pujian istana, didaktika politik, dan narasi historis, dengan latar hubungan Aceh yang luas—termasuk jejaring dengan Portugis, Cina, dan lingkungan Turki Utsmani. Sejumlah kajian juga menyorot pengaruh tradisi historiografi Islam-Persia/Mughal dalam struktur kisahnya; bahkan ada pendapat bahwa penulisan Hikayat ini kemungkinan dikomisi oleh Sultanah Safiatuddin Syah, putri Iskandar Muda, untuk mengukuhkan memori dinastik. Kombinasi unsur panegirik dan catatan faktual inilah yang membuat teks ini penting bagi studi politik-keagamaan Asia Tenggara awal modern.
Secara kodikologis, hanya tiga naskah yang bertahan: dua di Leiden University Libraries (Or. 1954 dan Or. 1983) dan satu di Perpustakaan Nasional RI (sering dirujuk sebagai ML 421). Or. 1954 dianggap tertua dan paling lengkap (sekitar 1675–1700), sedangkan Or. 1983 adalah salinan bertarikh 1847 dalam “Bahasa Melayu Betawi”; kedua naskah Leiden telah didigitalkan dan dapat diakses publik, memudahkan penelitian filologi dan sejarah Aceh. Berkas nominasi UNESCO mencatat rincian kepemilikan dan kolaborasi lembaga, yang mempertegas urgensi preservasi, katalogisasi, dan diseminasi Hikayat Aceh sebagai warisan dokumenter dunia.

Babad Diponegoro – Ditulis Antara 1831–1832
Ditulis Pangeran Diponegoro dalam pengasingan sekitar 1831–1832, Babad Diponegoro merekam pengalaman personal dan pandangan politik-batin tokoh sentral Perang Jawa. Naskah ini sering dipandang sebagai “dokumen ego” paling awal dalam kesusastraan Jawa modern karena memadukan bentuk otobiografi dengan gaya penulisan babad yang akrab bagi pembaca Jawa. UNESCO memasukkannya ke International Register pada 2013 sebagai dokumen tak tergantikan untuk memahami resistensi antikolonial dan dunia intelektual Jawa abad ke-19.
Secara kodikologis, naskah utama tersimpan di Perpustakaan Nasional RI dan lembaga-lembaga mitra di Belanda; ada pula terjemahan awal ke bahasa Belanda yang memperluas jangkauan pembaca Eropa. Beragam salinan dan transliterasi memungkinkan perbandingan varian bacaan serta studi paleografi dan ortografi (termasuk penggunaan tulisan Pegon/Jawa) dalam konteks penyalinan naskah abad ke-19. Berkas nominasi UNESCO memaparkan konteks historiografis dan signifikansi Babad sebagai sumber primer yang unik.

Tambo Tuanku Imam Bonjol (TTIB) – Ditulis Sekitar Abad Ke-19
Tambo Tuanku Imam Bonjol merekam pengalaman dan pandangan Tuanku Imam Bonjol serta konteks Perang Padri di Minangkabau abad ke-19. Dalam tradisi Minangkabau, “tambo” adalah kisah sejarah-genealogis yang memadukan memori kolektif, adat, dan legitimasi politik; naskah TTIB menonjol karena fokusnya pada pergulatan adat–agama serta intervensi kolonial pada periode kritis.
Pada 2024, TTIB ditetapkan ke Memory of the World Regional Register Asia–Pasifik (MOWCAP) dan ditampilkan oleh UNESCO Bangkok sebagai salah satu dari 20 inskripsi baru siklus 2024. Status regional ini memperkuat pengelolaan konservasi dan akses publik, sekaligus menandai posisi TTIB sebagai simpul penting dokumentasi perlawanan dan dinamika sosial-politik Sumatra Barat pada abad ke-19.

Sumber
- ANRI. (2025). Indonesia catatkan lima warisan dokumenter Indonesia dalam Register Internasional Memory of the World UNESCO. MOW Indonesia
- ANRI. (n.d.). Babad Diponegoro or Autobiographical Chronicle of Prince Diponegoro (1785–1855)… (profil nominasi). MOW Indonesia
- ANRI. (n.d.). Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian (profil nasional). MOW Indonesia
- ANRI. (n.d.). The Tambo Tuanku Imam Bonjol Manuscript (profil regional MOWCAP). MOW Indonesia
- ANRI. (n.d.). Naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol (profil nasional). MOW Indonesia
- ANRI. (2021). Hikayat Aceh — Nomination Form (PDF). MowidMOW Indonesia
- Fine Books. (2023, Mei). UNESCO Status for First Voyage Around the Globe, Hikayat Aceh, and Augustine Gospels. Fine Books & Collections
- JAIF. (n.d.). Webinar on World Documentary Archives, Memories and Heritage (ACHDA Phase 2, dukungan JAIF). jaif.asean.org
- LUL. (2017, 27 Juli). La Galigo manuscript – UNESCO heritage – digitally available. library.universiteitleiden.nl
- LUL Digital Collections. (n.d.). I La Galigo in context. digitalcollections.universiteitleiden.nl
- LUL — In the Media. (2023, 18 Mei). UNESCO recognizes… Hikayat Aceh as World Heritage. library.universiteitleiden.nl
- LUL — Special Collections. (n.d.). UNESCO World Heritage (Babad Diponegoro; Hikayat Aceh). library.universiteitleiden.nl
- Playbill. (2005, 1 Apr). Lincoln Center Announces Festival Lineup for 2005. Playbill
- Playbill. (2005, Juli). Visions of Creation (feature U.S. premiere I La Galigo). Playbill
- Robert Wilson. (n.d.). I La Galigo (lembar produksi). Robert Wilson
- UNESCO. (2011). La Galigo — Memory of the World (International Register). UNESCO
- UNESCO. (2013). Babad Diponegoro or Autobiographical Chronicle of Prince Diponegoro (1785–1855)… (International Register). UNESCO
- UNESCO. (2023). The Hikayat Aceh — Three manuscripts on life in Aceh… (International Register). UNESCO+1
- UNESCO. (2025). Register 2025 — 74 new items (termasuk SSKK & Works of Hamzah Fansuri). UNESCO+1
- UNESCO Articles. (2023, 7 Sep). New Inscriptions on the Memory of the World Register from Indonesia and Malaysia. UNESCO+1
- UNESCO Bangkok / MOWCAP. (2025, 28 Mei). UNESCO’s MOW Regional Register inscribes 20 new items… (siklus 2024; mencakup Tambo Tuanku Imam Bonjol). UNESCO
Eksplorasi konten lain dari Tinta Emas
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.